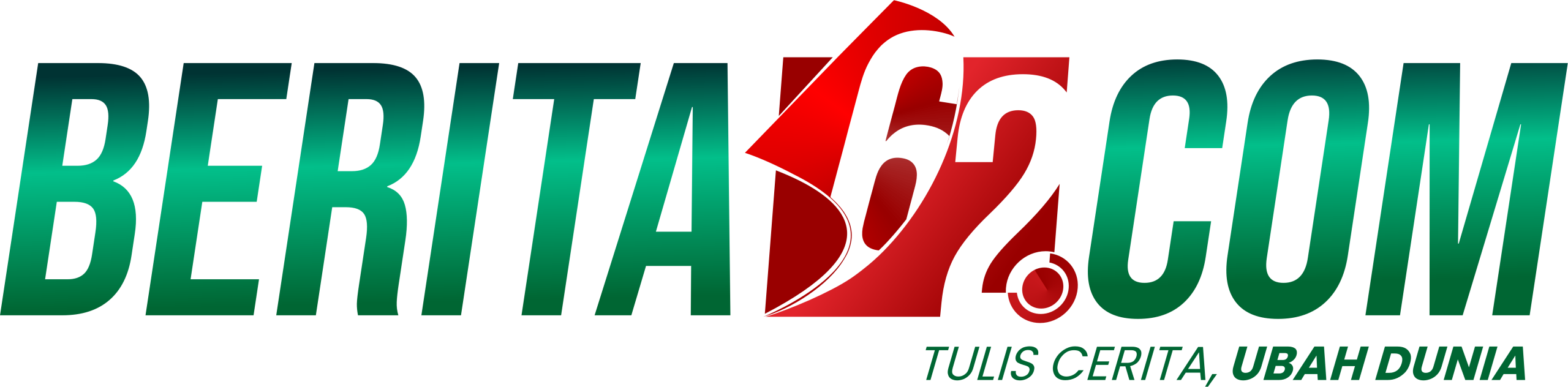BERITA62.COM – Burung itu kecil. Bulu cokelat kusam, paruh pendek, dan geraknya lincah. Setiap pagi ia hinggap di atap rumah, di tepi sawah, atau di kabel listrik, seperti makhluk remeh yang nyaris tak pernah diperhitungkan. Namanya burung gereja, Passer montanus, teman lama manusia yang hidup berdampingan sejak ribuan tahun lalu.
Namun pada akhir dekade 1950-an, di China, burung kecil ini berubah status. Dari bagian alam yang biasa, ia menjelma menjadi “musuh negara”.
Pada 1958, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, pemerintah China meluncurkan sebuah gerakan nasional bernama Four Pests Campaign. Empat makhluk ditetapkan sebagai hama yang harus dimusnahkan demi meningkatkan kesehatan dan produksi pangan: tikus, lalat, nyamuk dan burung gereja.
Burung gereja dituduh sebagai pencuri hasil panen. Ia dianggap memakan biji padi dan gandum yang seharusnya menjadi jatah rakyat. Logikanya sederhana: jika burung dihilangkan, panen akan meningkat.
Maka dimulailah sebuah pembasmian massal yang melibatkan jutaan orang. Sarang dirusak, telur dihancurkan. Di desa-desa dan kota-kota, warga diperintahkan memukul panci, wajan dan alat logam lainnya berjam-jam lamanya. Burung-burung dipaksa terus terbang tanpa henti, hingga kelelahan dan jatuh mati dari langit.
Dalam waktu singkat, populasi burung gereja anjlok drastis. Di sejumlah wilayah, spesies ini nyaris lenyap.
Awalnya, kebijakan itu dianggap berhasil. Ladang tampak lebih “aman”.
Namun alam menyimpan perhitungan sendiri.
Burung gereja ternyata bukan hanya pemakan biji-bijian. Dalam kesehariannya, ia juga memangsa serangga, ulat, wereng dan belalang kecil, yang justru merupakan hama utama tanaman. Ketika burung-burung itu menghilang, keseimbangan alam runtuh perlahan tapi pasti.
Serangga berkembang biak tanpa kendali. Belalang menyerbu ladang-ladang. Tanaman yang sudah rapuh oleh kebijakan pertanian yang keliru tak mampu bertahan. Panen gagal, dari desa ke desa.
Bencana itu terjadi bersamaan dengan kebijakan Great Leap Forward yang memaksa kolektivisasi ekstrem, teknik pertanian yang tidak ilmiah, serta laporan hasil panen palsu dari pejabat lokal yang takut dianggap gagal. Negara tampak makmur di atas kertas, tetapi lumbung-lumbung desa kosong.
Gabungan dari semua faktor tersebut memicu tragedi yang kini dikenal sebagai Great Chinese Famine. Antara 1959 hingga 1961, puluhan juta orang kelaparan. Para sejarawan memperkirakan jumlah korban meninggal berkisar antara 15 hingga lebih dari 40 juta jiwa, bukan karena satu kesalahan tunggal, melainkan karena rangkaian kebijakan yang mengabaikan realitas alam dan manusia.
Di tengah krisis itu, pemerintah China akhirnya mengakui kekeliruan. Burung gereja dicabut dari daftar Empat Hama dan digantikan oleh organisme lain. Ada pula upaya memulihkan populasi burung, termasuk mendatangkannya dari luar negeri. Namun keseimbangan ekosistem tidak bisa dipulihkan seketika. Kerusakan telah terlanjur terjadi, dan jutaan nyawa sudah melayang.
Hari ini, burung gereja kembali hinggap di atap-atap rumah di China, seperti di banyak belahan dunia lain. Ia kembali menjadi makhluk kecil yang nyaris tak diperhatikan. Namun sejarah pernah mencatatnya, bukan sebagai penyebab tunggal bencana, melainkan sebagai simbol bagaimana kesombongan manusia dalam membaca alam dapat berujung pada tragedi kemanusiaan.
Kisah burung gereja mengajarkan satu hal sederhana namun mahal harganya: alam bukan musuh yang bisa ditundukkan dengan perintah dan propaganda. Ia adalah sistem rumit yang saling terhubung. Ketika satu simpul diputus tanpa pengetahuan dan kehati-hatian, seluruh jaring kehidupan bisa runtuh, dan manusia sering menjadi korban terakhir dari kesalahannya sendiri. (BME-1)